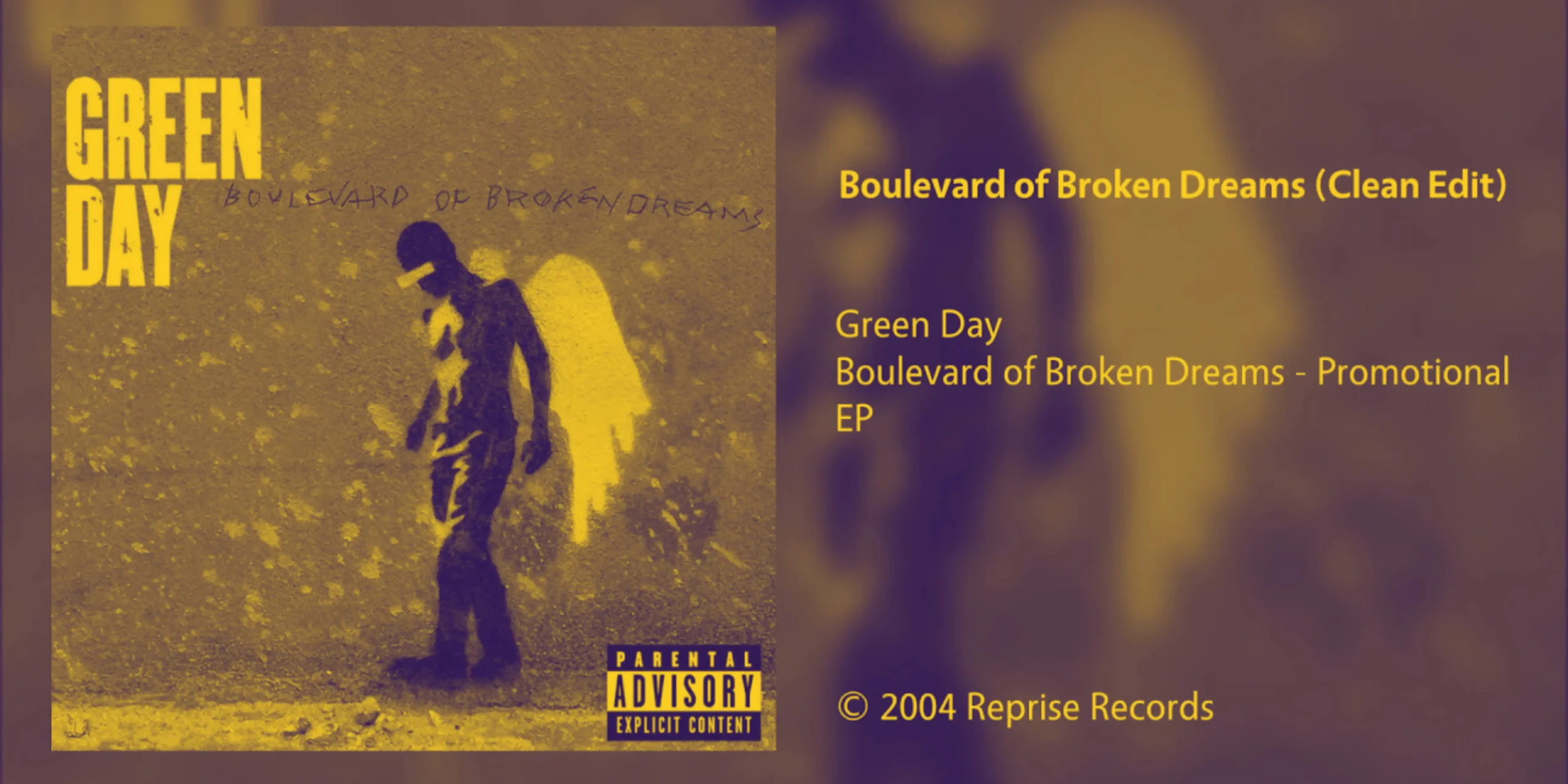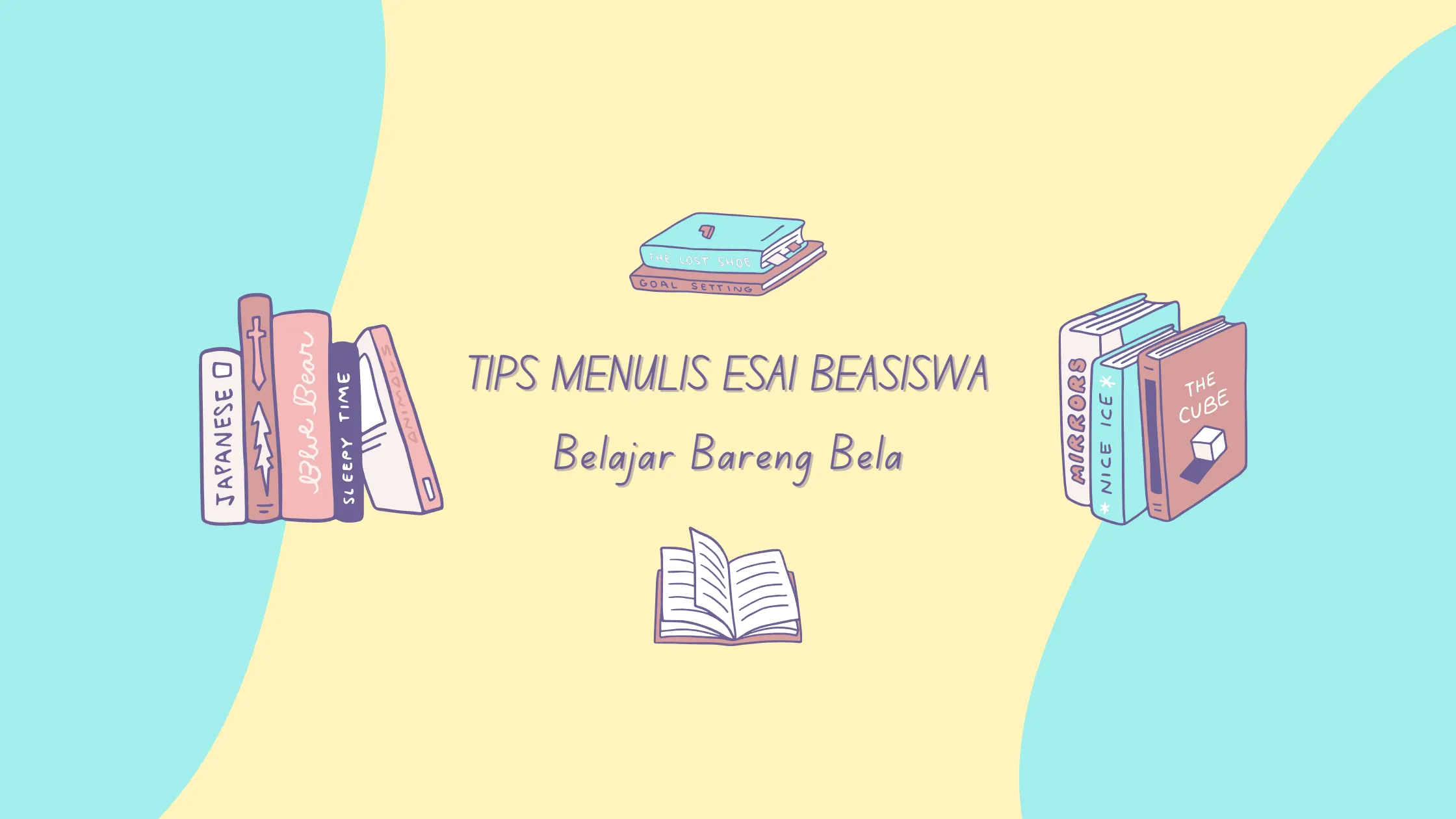Rebeka dan Kisah Di Atas Kertas Putih

Sudah sekian waktu kertas putih itu dibiarkan tergeletak di atas meja di sampingnya Rebeka masih menggerutu sana-sini mencari pena. Dia mengutak-atik laci meja berkali-kali, namun pena jahanam itu sulit ditemukan. Rebeka mungkin merasa bersalah pada kertas di atas meja itu. Dia sudah dilepas kosong tanpa tulisan dan Rebeka hanya membubuhkan air mata di atasnya. Kertas itu barangkali menggubris kalau menyeka air mata adalah bukan tugasnya. Bila demikian Rebeka pasti tidak akan peduli. “Persetan denganmu!! Intinya aku aman.” Kira-kira demikian pembelaan Rebeka. Namun kertas tak mau mengalah di awal. Dia merasa diremehkan oleh Rebeka. Kodratnya sebagai kertas mungkin akan segera hilang bila tidak melawan perlakuan gadis remajanya ini. Dia menghela perbuatan Rebeka dengan belasan alasan. “Apa pula alasanmu mengerikan pipi dengan kertas? Kau bisa mengambil sapu tangan atau berbagi pada orang lain sebagai sahabat.”
“Tidak!! Sedikitpun kau tak mengerti keadaanku.”
Seusai silang pendapat keduanya tak berani memulai percakapan atau sekadar menjernihkan keadaan. Rebeka melanjutkan pencarian yang sempat terhenti. “Untuk apa pula kau mencarinya?” Rebeka berpura tidak mendengar. Kali ini dia lebih serius. Sekali lagi, beberapa tetes air mata jatuh dari pipi Rebeka. Kertas telah habis kesabaran saat ini. Dia menantang Rebeka dan mengutuk perbuatan kejinya. Alih-alih mendapat penjelasan, kertas malah diserang bertubi-tubi oleh air mata Rebeka. “Apa salahku!?”
“Aku hanya ingin kau mengerti keadaanku.”
“Tapi tidak dengan cara seperti ini.”
“Tidak ada cara lain!”
“Pasti ada, tidak mungkin tidak.”
Rebeka bangkit dari duduknya lalu bergegas menuju kamar. Lima menit setelahnya dia keluar menenteng bulatan kain batik di tangan kiri dan pena di tangan yang satu. Yahh.. Itu lebih bermartabat, batin kertas setelah melihat pena di tangan Rebeka.
Mulailah Rebeka berkisah pada kertas.
Hari itu gerombolan burung gereja hinggap di depan rumah. Seperti biasa mereka bernyanyi dalam bahasa burung. Biasanya aku adalah orang paling setia mendengar kawanan itu bernyanyi. Biasanya aku bersama kursi goyang senantiasa terhibur oleh paduan kicauan itu. Biasanya pula aku tertidur. Biasanya itu terjadi tidak hari ini. Hari ini aku seperti orang yang paling benci dengan suara nyanyian itu. Mereka seperti menertawakan kemalangan yang aku alami. Kursi yang biasa menemani aku menikmati nyanyian para burung sudah kubuang di gudang. Aku merasa orang paling malang saat ini. Tak bisa kubayangkan selanjutnya hidup tanpa seorang ayah. Tak mampu lagi aku menikmati kicauan burung gereja sebagai seorang yatim. Jangan datang lagi, jangan berkicau lagi di depan rumahku.
Baru sebulan setelah kepergian ayah aku mulai menjalani hari seperti sebelum-sebelumnya. Tak ada lagi ekspresi murung saat burung-burung gereja terakhir kali terlihat di depan rumah. Aku dan ibu harus terbiasa dengan ibu harus terbiasa dengan keseharian tanpa tulang punggung keluarga. Tentu saja kami sangat kesulitan finansial setelah ketiadaan ayah. Ibu bekerja lebih lama dari sebelumnya. Ketika ayah masih hidup ibu bekerja separuh hari di sebuah jasa laundry. Untuk saat ini biaya kehidupan kami jauh lebih besar ketimbang uang yang ibu terima dari sana. Maka sepulang dari tempat loundry ibu tak langsung pulang rumah. Katanya, dia diterima di rumah produksi daging ayam. Dengan begitu kesulitan kami bisa sedikit teratasi.
Gerbang sekolah sudah dikerumuni banyak siswa. Seperti biasa, kegiatan pemeriksaan rutin dilakukan. Satu per satu dicek mulai dari kaki hingga rambut. Semua harus rapi, tidak boleh tidak. “Ini akan membentuk karakter kalian di masa depan.” Ujar kepala sekolah ketika pengibaran bendera pekan lalu. Aku sangka hari ini sama seperti biasanya, namun cerita berjalan lain. Warga sekolah digemparkan dengan berita ditangkapnya pak lurah karena dugaan menerima suap dari pihak kedinasan. Sebagian telinga bersorak mendengar kabar ini. Dalam beberapa hari ke depan topik pembicaraan akan selalu sama: kabar pak lurah. Tak butuh waktu lama, beberapa mulut bahkan sudah start lebih awal. “Begitulah kalau terlalu hedonisme, apa-apa dihalalkan.” Ujar seorang siswi di pojok sana. “Kasihan dengan si Nita. Orang tua yang buat, anaknya kena imbas.” Balas teman di sampingnya yang tampak lebih simpatik. “Ah, orang tua anak sama aja!”
Begitulah. Sejak kejadian menimpa ayah dan keluarga, Nita tak pernah muncul lagi di sekolah. Pihak sekolah sudah menyurati beberapa kali tapi nihil balasan. Itu kabar terakhir yang kami dengan tentang anak mantan lurah itu dan keluarganya. Dan kemarin kami dikejutkan dengan berita Nita telah dinikahi oleh seorang kontraktor dari kedinasan. Ya, usianya terbilang muda untuk urusan rumah tangga, menurutku. Soal sang ibu, kami tak mendapat kabar apa-apa.
Di rumah aku ceritakan kisah tadi pada ibu. Kelihatannya dia tidak tertarik dengan topik semacam itu. Matanya terus mengarah pada piring dan mulut mengunyah makanan. Sekali-kali merespons, itu pun bukan dengan kata-kata tapi dengan isyarat agar aku menghabiskan makanan. “Udah, cukup tahu aja tidak usah dibahas. Setiap keluarga pasti punya aib.” Seolah mengerti dengan perkataan ibu, aku pun menghabiskan makan malamku.
Malam berikutnya aku menikmati makan malam seorang diri. Di atas meja bundar ini hanya ada aku seorang, tanpa ibu. Aku harus terbiasa dengan keadaan semacam ini. Ya, ibu tidak bisa lagi ada terus bersamaku sepanjang waktu bahkan untuk makan malam bersama sekalipun. Ibu akan makan lebih awal sebelum aku selesai bimbingan sore di sekolah. “Ibu harus ambil jam tambahan di rumah produksi ayam. Uang kita tidak cukup.” Katanya memberi pengertian. Aku paham saat ini kami memerlukan lebih banyak uang untuk beberapa hal terutama untuk biaya bimbelku dan uang semester akhir sekolah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ingin membantu ibu tapi dengan cara apa? Putus sekolah lalu kerja? Aku belum siap.
“Bu, batas uang bimbel minggu ini.” Kataku di pagi itu sebelum berangkat sekolah. Ibu hanya mengangguk sembari mengosongkan piring makannya. Seusai sarapan, kami berdua siap menuju tempat Masing-masing. Ibu ke tempat loundry sedangkan aku ke sekolah. “Nanti ibu usahain, yah.” Ujarnya sebelum berangkat. Kami berdua berpisah di depan pintu rumah dan akan bertemu besok pagi. Akhir-akhir ini ibu pulang larut saat aku sudah tertidur.
Bimbingan belajar untuk Ujian Nasional semakin lama semakin memberatkan. Kadang waktu bimbingan ditambah hingga satu jam atau bahkan sampai dua jam seperti sekali ini. Lebih memberatkan ketika ditambah tugas di akhir kegiatan. Beginilah aku menyusuri lorong jalan sendiri. Lampu jalan hanya satu dua yang tetap bersinar, meskipun agak samar. Selebihnya tidak kurang hanya aksesoris jalan. Suara percik lampu rusak di pinggir jalan kini semakin terdengar jelas. Beberapa mengeluarkan percikan api. Namun sesaat setelah itu kutemukan beberapa orang pria dewasa berkumpul di depan sana. Aku mengira dalam kehampaan cahaya itu ada tiga pria dewasa. Mereka saling bercakap satu sama lain. Yang satu sepertinya mengeluarkan kata-kata manis seperti menggoda seorang gadis. Pola percakapan mereka terdengar asyik. Tak ada kekejaman dan paksaan di sana. Mimpi buruk! Mereka memang tatapanku. Aku melihat di sana. Ya, tidak salah lagi. Aku menemukan seorang wanita dalam kepungan para pria. Bahkan sebelum mereka membuka mulut dan menggerakkan kaki aku sudah lebih dulu kabur menjauh, menuju rumah. Aku termangu sesaat memikirkan apa yang barusan kulihat. Di dalam rumah kudapati ibu belum juga pulang.
“Bu, batas uangnya besok. Kata pak Ridho kami belum bisa melanjutkan bimbingan kalau besok belum lunas.” Aku mengawali pembicaraan di atas meja makan itu. Ibu tersenyum padaku. Lebih tepatnya senyum kasihan. Dia berjanji besok pagi uang itu sudah ada. “cepat habiskan sarapanmu. Ibu sudah agak telah.”
“Bu, aku melihat istri pak lurah semalam.”
“maksud kamu?” Ibu memberi perhatian pada ucapanku. Piring di atas meja itu dia lepaskan.
“Iya bu. Semalam aku pulang agak lambat dan di depan ruko-ruko itu aku dapati ibu lurah dikerumuni para pria.”
“Ibu nggak ngerti!”
“Itu loh bu wanita malam,” Aku melanjutkan, “maksud aku, kami pulang telah semalam karena nambah waktu satu jam. Terus di jalan aku lihat bu lurah bersama beberapa pria.”
“Bilang pada gurumu, cukup pulang selarut itu!”
Karena banyak siswa mengeluh penambahan waktu kemarin, hari ini kami sepakat memulai Bimbingan sejam lebih awal. Tentu saja hal ini dilakukan supaya selesai sebelum larut malam. Pembelajaran berjalan lancar, tak ada yang berubah. Seperti biasa di sesi akhir kami dibagi ke beberapa kelompok. Aku sekelompok dengan Niny, sahabat karibku. Di tengah diskusi aku mengeluarkan apa yang sedari tadi menjadi unek-unekku. Aku bertanya padanya soal ibu lurah. “Kamu tahu juga?!” Aku menganga mendengar pernyataan Niny. Sejak kapan mereka tahu. Ataukah soal ibu lurah sudah menjadi rahasia umum di sekolah. Aku begitu kaget dengan jawaban itu. “Sejak suaminya ditangkap, semua harta mereka disita oleh negara. Ibu lurah kesulitan mencari uang dan dengan cara itu dia mendapatkannya.”
Aku Selesaikan tugas sekolah lebih awal sebelum ibu pulang. Aku tidak menunggu besok pagi ibu memberikan uang bimbingan. Makan malam pun aku menunggu ibu pulang. Sudah berapa lama aku tidak pernah bersamanya saat makan malam. Malam kelihatan cerah. Bintang-bintang di langit bertebaran di mana-mana. Bulan bersinar seperempat dari bentuknya. Tidak heran suasana di depanku agar remang-remang. Di ujung jalan sana aku masih terbayang dalam kejaran para pria dewasa itu. Rahang mereka mengeras seperti hendak melahap seseorang, dan yang jelas itu aku. Tanpa kusadari jalan besar itu sudah di depan mata. Aku sendiri merasa terhipnotis oleh ujung jalan ini. Ya, tepat di bawah lampu jalan redup ini aku berdiri.Di sekeliling tidak ada siapa-siapa. Namun di ujung sana beberapa pria sedang tawa terbahak-bahak. Aku kira mereka mabuk dan jelas demikian. Mungkin juga, perasaan ku saja, ibu lurah di sana.Benar dugaanku. Ada perempuan di sana, tertawa. Tapi bukan satu saja, melainkan dua. Mereka mendekat. Aku menyingkir ke luar trotoar, di depan ruko, tempat yang gelap. Mereka tak dapat melihatku di sini. Semakin mendekat dua muka itu tidak asing lagi bagiku. Ya lebih dekat, sedikit lagi aku bisa mengenalnya dengan jelas.Itu dia tidak salah lagi. Ternyata ini yang dia lakukan di belakang!
“Cukup” Kata Rebeka. Namun kertas belum menemukan inti persoalannya. Sejurus kemudian dia menggerutu meminta penjelasan dari Rebeka. Rebeka hanya diam. Tersenyum pun tidak. Sesaat setelahnya dia merentangkan kain batik pada ujung kipas. Kertas malah tambah bingung dibuatnya. Ada apa gaung si kertas. Rebeka tetap tak ingin menjawab.
“Kamu tahu kenapa ibu belum pulang?”
“Seturut ceritamu dia bekerja.” Tepat, kata Rebeka.
“Dan Niny pasti tahu apa pekerjaan ibu”
“Lalu?”
“Aku dan ibu akan disebut dimana-mana”
Tanpa menunggu jawaban kertas, Rebeka memasukkan kepalanya dalam lubang kain itu. Kemudian menggantung.
Sebelum teman-temannya tahu soal ibunya, Rebeka harus menghilang lebih awal. [*]